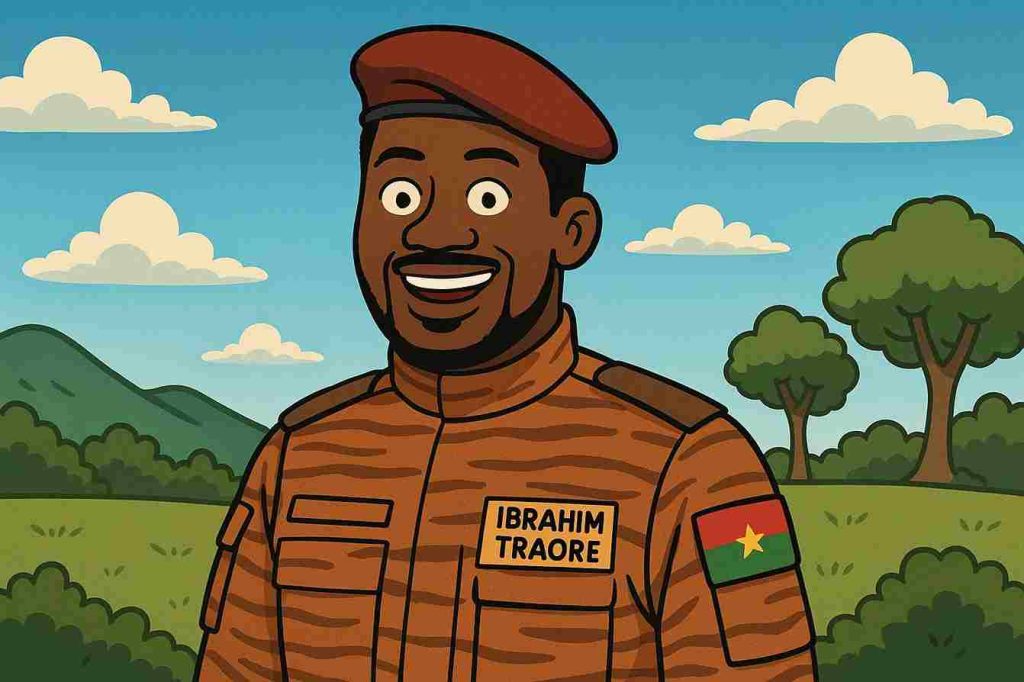
Ibrahim Traoré
“Kasus Burkina Faso mengingatkan kita bahwa penyeimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil adalah tantangan abadi bagi setiap negara. Seringkali, atas nama keamanan nasional, hak-hak sipil dikesampingkan, membuka pintu bagi otoritarianisme. Indonesia harus terus memperkuat institusi demokratisnya agar tidak kembali terjerumus pada praktik-praktik represif dan pembatasan kebebasan,”
SUPREMASI.ID~Medan || Kemunculan Ibrahim Traoré sebagai pemimpin militer Burkina Faso melalui kudeta telah memicu gelombang perhatian global. Bukan hanya karena usianya yang terbilang muda, tetapi juga karena lantangnya retorika anti-Barat dan semangat Pan-Afrikanisme yang ia gelorakan. Fenomena ini, yang berakar kuat pada warisan eksploitasi kolonial dan tantangan keamanan internal yang akut, menghadirkan cermin berharga bagi Indonesia—sebuah negara yang juga tak henti berjuang melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu kolonialnya.
Sejak mengkudeta kekuasaan pada September 2022, Kapten Ibrahim Traoré dengan cepat memposisikan diri sebagai simbol perlawanan baru di kawasan Sahel yang bergejolak. Dalam narasi yang ia bangun, Burkina Faso, layaknya banyak negara pasca-kolonial lainnya, terperangkap dalam lingkaran setan eksploitasi dan ketergantungan ekonomi yang telah berlangsung puluhan tahun. Kegagalan pemerintah sipil sebelumnya dalam menumpas pemberontakan jihadis yang merajalela pun menjadi justifikasi utama di balik kudetanya.
“Generasi saya tidak memahami ini: bagaimana bisa Afrika, yang begitu kaya akan kekayaan, menjadi benua termiskin di dunia saat ini?” ujar Traoré dalam sebuah pidato yang menjadi viral, sebuah seruan tajam yang menyoroti paradoks “kutukan sumber daya” yang melanda banyak negara bekas jajahan. Pidatonya ini secara gamblang menunjuk pada struktur ketergantungan yang diwarisi dari era kolonial, di mana kekayaan alam diekstraksi tanpa henti untuk kepentingan metropol, menyisakan kemiskinan dan ketidakstabilan di tanah asalnya.
Struktural Ketergantungan dan Cengkeraman Oligarki Lokal
Analisis mendalam terhadap kondisi ini mengungkapkan bahwa kolonialisme secara sistematis menciptakan apa yang disebut “struktural ketergantungan.” Melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada ekstraksi bahan mentah, negara-negara penjajah memastikan bahwa bekas koloni mereka tetap menjadi pemasok komoditas mentah dan pasar yang loyal bagi produk manufaktur mereka. Pola ekonomi ini, sayangnya, berlanjut bahkan setelah kemerdekaan, diperparah dengan kemunculan oligarki lokal.
“Kasus Burkina Faso terang-benderang memperlihatkan bagaimana warisan kolonialisme tidak hanya meninggalkan batas-batas geografis yang artifisial, tetapi juga membentuk struktur ekonomi yang sangat rentan dan melahirkan elit lokal yang kerap bersekutu dengan kepentingan asing,” demikian analisis seorang pengamat sosial politik yang sering mengkritisi isu-isu kebangsaan dan geopolitik, Shohibul Anshor Siregar.
Oligarki ini, kata Siregar, seringkali menguasai sektor-sektor kunci dan sumber daya negara, menjadi penghalang utama bagi distribusi kekayaan yang adil dan pembangunan yang inklusif.
Siregar mengungkapkan, ketika kekayaan alam, seperti tambang emas di Burkina Faso, tidak dikelola secara transparan dan berkeadilan untuk kepentingan rakyat, ia justru rentan menjadi sumber korupsi dan konflik. “Ini adalah resource curse dalam wujud paling nyata,” kata Siregar.
“Kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah, justru bertransformasi menjadi kutukan yang memicu perebutan kekuasaan, korupsi endemik, dan pada akhirnya, pemiskinan sistemik bagi rakyat banyak.” imbuhnya.
Retorika Anti-Barat dan Pergeseran Geopolitik di Sahel
Siregar melihat, retorika anti-Barat yang diusung Traoré, ditambah keinginannya untuk menjalin aliansi baru dengan Rusia serta mitra non-Barat lainnya, adalah langkah nyata untuk mendiversifikasi hubungan geopolitik dan mengurangi ketergantungan historis pada kekuatan tradisional Barat, terutama Prancis sebagai bekas penjajah. Ini mencerminkan kebangkitan sentimen Pan-Afrikanisme yang mendambakan kemandirian sejati dan kedaulatan penuh bagi benua Afrika.
Semangat anti-kolonial dan politik bebas aktif adalah fondasi yang sangat dikenal oleh Indonesia. “Di era Presiden Soekarno, Indonesia menjadi pelopor Gerakan Non-Blok, sebuah upaya berani untuk tidak didikte oleh kekuatan mana pun di tengah bipolaritas Perang Dingin. Ini adalah manifestasi kuat dari hasrat fundamental untuk kedaulatan penuh,” ujar Siregar, merefleksikan sejarah diplomasi Indonesia. “Namun, penting untuk diingat bahwa ada perbedaan besar dalam konteks implementasi dan legitimasi politik antara kedua kasus,” tambahnya.
Cermin Bagi Indonesia: Legitimasi, Demokrasi, dan Tata Kelola Sumber Daya
Siregar mengatakan, bagi Indonesia, pengalaman Burkina Faso di bawah Ibrahim Traoré adalah cermin penting yang menawarkan pelajaran berharga:
Pertama, Legitimasi Kekuasaan. Sementara Traoré memperoleh kekuasaan melalui kudeta militer yang secara inheren tidak konstitusional dan berpotensi rapuh, Indonesia berhasil membangun negara-bangsa di atas dasar konstitusi dan perjuangan rakyat yang diakui secara luas. Meskipun pernah mengalami periode otoriter Orde Baru di bawah Soeharto yang juga berasal dari militer dan mengedepankan stabilitas, fondasi konstitusional Indonesia memungkinkan transisi menuju demokrasi yang lebih kuat pasca-Reformasi 1998.
“Ini adalah pelajaran krusial,” tegas Siregar. “Stabilitas yang dibangun di atas kudeta cenderung rapuh dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Demokrasi, meskipun sering bergejolak dan penuh dinamika, menawarkan legitimasi politik yang jauh lebih kuat dan mekanisme akuntabilitas yang lebih baik bagi rakyat.” imbuhnya.
Kedua, Lintasan Demokratisasi. Indonesia telah menempuh perjalanan yang signifikan menuju konsolidasi demokrasi, ditandai dengan pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan pers yang relatif tinggi, dan penguatan lembaga-lembaga checks and balances.
“Kasus Burkina Faso mengingatkan kita bahwa penyeimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil adalah tantangan abadi bagi setiap negara. Seringkali, atas nama keamanan nasional, hak-hak sipil dikesampingkan, membuka pintu bagi otoritarianisme. Indonesia harus terus memperkuat institusi demokratisnya agar tidak kembali terjerumus pada praktik-praktik represif dan pembatasan kebebasan,” papar Siregar.
Ketiga, Tata Kelola Sumber Daya Alam. Sebagai negara yang sangat kaya sumber daya alam, Indonesia juga tak luput dari tantangan “kutukan sumber daya”. Pengelolaan yang tidak transparan, praktik korupsi, dan ketidakadilan dalam distribusi hasil di sektor pertambangan, perkebunan, atau perikanan dapat memicu ketidakpuasan sosial dan memelihara kemiskinan sistemik, mirip dengan apa yang terjadi di Burkina Faso.
“Frustrasi Traoré tentang kemiskinan di tengah kekayaan adalah peringatan keras bagi kita semua,” kata Siregar.
“Indonesia harus memastikan bahwa kekayaan alamnya benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat secara merata, bukan hanya segelintir elit atau korporasi. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum yang tegas dalam pengelolaan sumber daya adalah kunci fundamental untuk menghindari jebakan ini dan mewujudkan keadilan ekonomi.” tegasnya.
Siregar memandang, fenomena Ibrahim Traoré di Burkina Faso bukan sekadar cerita lokal di Afrika, melainkan sebuah narasi universal tentang perjuangan negara-negara pasca-kolonial untuk mencapai kedaulatan sejati, keadilan, dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Bagi Indonesia, ini adalah pengingat bahwa perjalanan menuju cita-cita tersebut adalah proses yang tak pernah usai, yang menuntut kewaspadaan abadi terhadap warisan masa lalu dan komitmen teguh pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kemakmuran yang merata.,” pungkasnya. (*)

